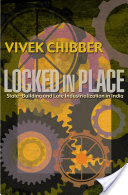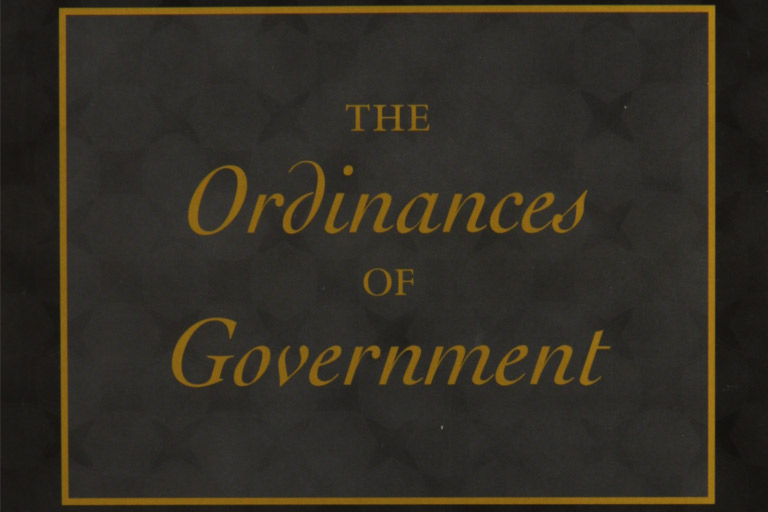Mesjid di pusat kota Beureuneun, Pidie, belum selesai dibangun. Compton yang datang dari Banda Aceh, melihat bangunan itu dari jauh, dan membayangkan perasaan yang sedang dialami oleh Daud Beureuh. Tujuannya datang ke kota itu untuk menemui Daud Beureuh, ulama sekaligus pemimpin politik Aceh. Beureuh sedang gusar dan frustasi. Negeri yang dia bela mati-matian di zaman revolusi fisik, ternyata tidak seiring sejalan dengannya kemudian hari. Compton hendak melihat kegusaran itu dari dekat. Kegusaran, yang dibaca dari Jakarta akan menimbulkan gesekan yang tidak kecil.
Dari dekat, Compton menyaksikan, Daud Beureueh yang ditemuinya lebih mirip pensiunan tentara ketimbang ahli agama. Badannya kurus dan kokoh. Compton memperhatikan betul gesture pemimpin yang paling dihormati sejak tahun 1930-an itu. Memperhatikan apa yang akan dilakukannya ketika Aceh yang berjasa, tidak mendapatkan balasan setimpal. Balasan yang diyakini oleh pemimpin Aceh kala itu, dapat mengembalikan daerah ini jaya seperti dalam masa lalunya
“Kami ingin Aceh ini seperti zaman Iskandar Muda,” kata Daud Beureuh dengan masygul. Ucapan disampaikannya dengan mendalam, sampai-sampai membuat pengikutnya yang hadir pada pertemuan itu menjadi menjadi kikuk.
Fragmen menarik ini dapat dibaca di buku Boyd R. Compton, Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton (1992). Buku yang diterbitkan oleh LP3ES ini adalah kesaksiannya, atas peristiwa politik di zaman ketika nasion sedang dibangun. Buku ini memuat banyak cerita, tentang hiruk pikuk politik. Tentang Aceh dan Daud Beureuh. Mengenai Sukarno. Islam yang terus mencari jalan. Dan, Indonesia yang terus mencari keseimbangan. Buku yang sebenarnya berasal dari surat-suratnya itu, kemudian menjadi warisan Compton.
Compton berada di Indonesia untuk menyelesaikan studinya, namun gagal. Sehingga dia tidak dikenal sebagai ahli politik. Namun surat suratnya itu menjadi penting karena menjelaskan hal yang luput dari peneliti lain tentang Indonesia.
“Kendatipun Compton gagal menulis disertasinya — analisa-analisa politik Indonesia tahun lima puluhan –dalam bentuk surat-surat panjangnya –toh sangat berharga untuk disimak,” tulis Fachry Ali dalam pengantarnya.
Dari Compton kita melihat Beureuh sebagai perwujudan imaji terdalam dalam masyarakat Aceh: bahwa kembali ke masa lalunya yang agong adalah pra-syarat untuk kemajuan di masa mendatang. Iskandar Muda tentunya dimaknai sebagai raja besar yang memiliki kekuatan dan menjalankan syariat Islam. Apalagi dengan cerita, bahwa dia telah menghukum putera mahkotanya, karena melanggar syariah. Sebuah tindakan heroik yang dikenang melalui hadih maja “mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat ta mita.” Adat di sini ditafsirkan sebagai penegakan syariah Islam.
Aceh oleh generasi Beureuh dibangun dengan imaji dan ingatan kolektif mengenai Islam, ketika generasi Beureuh berada di zaman yang saling silang. Hal yang diakibat bertemunya Aceh dengan kemajuan yang dibawa oleh bangsa Barat atas praktik kolonialisme. Perjumpaan itu yang dinamakan dengan modernisme. Sebuah ide yang menolak dan mengambil dari Barat sekaligus. Dari jalan Barat, generasi Beureuh memahami tentang Aceh yang baru. Lalu membangun apa yang diyakini dari masa lalunya; Islam. Tanpa Islam, maka bukan Aceh. Konstruksi itu dilakukan dengan baik oleh generasi Beureuh, dan diceritakan melalui kisah epos perang suci Aceh melawan Belanda, yang diwakili sosok Tgk. Chik di Tiro.
T.A. Talsya, wartawan cum sasterawan menyebut sosok ini yang memiliki perasaan meluap-luap untuk memimpin perjuangan melawan kaphe Belanda. “Dengan penuh kesadaran dan semangat anti Belanda (kafir) yang melupa-luap, beliau bersedia untuk memimpin perjuangan suci ini,” tulisnya.
Sosok ini pula yang menjadi inspirasi generasi Beureuh ketika mengobarkan semangat jihad, melalui maklumat ulama, 15-10-1945, untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia,
“…bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Almarhum Tgk. Chik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain.” (Hasjmy, 1984)
Bahkan atas nama Tgk. Chik di Tiro pula, PUSA menyusun sebuah memorandum politiknya, di tahun 1950, mengenai keabsahan ulama untuk memegang posisi kepemimpinan di Aceh yang kosong, akibat perang yang berkecamuk.
“…Karena itu, pendirian PUSA adalah jawaban terhadap kekosongan kepemimpinan. Maka PUSA mengambil alih kepemimpinan Aceh. Berdasarkan kenyataan bahwa ulama Tiro yang akhirnya memegang hak kepala negara Aceh, kebangkitan PUSA sebagai organisasi ulama telah sekaligus menjadi pewaris langsung dari kekuasaan sultan.” (Ali dkk, 2008)
Namun ironi, dengan nama Tgk. Chik di Tiro pula, Sukarno meyakinkan Daud Beureueh untuk mempertahankan proklamasi 1945. Bahwa peperangan yang berkobar-kobar dalam revolusi nasional, merupakan maksud perang yang digelorakan oleh Tgk. Chik di Tiro.
”Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Chik di Tiro dan lain-lain…” Pungkas Sukarno dalam dialognya dengan Daud Beureuh di tahun 1947 (El Ibrahimy, 1984).
Disebut ironi karena fragmen itulah yang menjadi titik anjak kemarahan berdekade antara Aceh dengan Jakarta. Maksud Aceh membantu mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia, guna mengembalikan Islam di Aceh seperti zaman Iskandar Muda. Dan apa yang telah ditunjukkan oleh Tgk. Chik di Tiro dalam peperangan suci. Namun yang terjadi, Aceh dilebur ke dalam provinsi Sumatera Utara. Hal yang kemudian memulai narasi perlawanan Aceh terhadap Jakarta.
Perlawanan pertama melalui Darul Islam, dipimpin oleh Daud Beureuh. Meletus tahun 1953 dan berhenti di tahun 1962, melalui upaya damai dan bermartabat, baik melalui Ikrar Lamteh dan Kongres Kerukunan Rakyat Aceh. Darul Islam adalah gerakan politik menuntut apa yang belum diberikan, hak untuk melaksanakan Syariat Islam. Hak tersebut diberikan melalui skema Daerah Istimewa Aceh.
Perlawanan kedua, melalui Gerakan Aceh Merdeka, 1976-2005, dipimpin oleh murid Daud Beureuh, Hasan Tiro. Berbeda dengan Darul Islam, perlawanan kali ini adanya perpindahan gagasan, dari islamisme ke (etno)nasionalisme. Gagasan yang dibangun dengan letupan bedil itu, akhirnya juga berhenti di meja perundingan. Berdamai di Helsinki. Lalu, kembali, otonomi khusus diberikan untuk Aceh. Perbedaannya, kali ini lebih besar wewenangnya yang diberikan, dibandingkan setelah penyelesaian peristiwa Darul Islam. Ada kebebasan untuk menampilkan eskpresi politik dan budaya lokal, penguasaan sumber daya alam, pembagian alokasi dana yang lebih besar dan wewenang luas untuk melaksanakan syariat Islam.
Pendeknya, perdamaian dari Helsinki telah membuka ruang politik yang lebar untuk segala ekspresi yang ada. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ide Syariat Islam malah semakin mendapatkan ruang politiknya, paska 2005, di saat ruang itu dibuka oleh gerakan yang tidak mengusung gagasan islamisme.
Tulisan ini[ref]Bagian ini telah dipublikasi di http://www.bung-alkaf.com/2017/12/08/gam-setelah-41-tahun-demokrasi-dan-ruang-politik-untuk-syariah/[/ref] hendak menjawab pertanyaan di atas melalui penelusuran secara genealogis.
Sejak memasuki abad kontemporer, Aceh telah membuka ruang untuk melakukan perbincangan antara gagasan Islam dengan nasionalisme. Cita-cita mengenai kejayaan Islam Aceh di masa lampau, kemudian dicoba terapkan dalam eksperimen politik modern. Melalui pertemuan dengan gagasan baru yang bernama Indonesia. Untuk itu, Aceh menjadikan Islam persyaratan utama ketika mendukung proklamasi Indonesia. Sehingga ketika Darul Islam Aceh itu terjadi, hal tersebut haruslah dilihat sebagai ungkapan politik untuk memasukkan Islam dalam kehidupan bernegara.
Perjumpaan Islam dan nasionalisme menjadi lebih tajam, ketika Hasan Tiro melakukan revisi terhadap gagasan kebangsaan Indonesia. Dia memasuki, bahkan berpindah dari gagasan islamisme kepada apa yaang disebut sebagai etnonasionalisme (Damanik, 2010). Untuk memperkuat gagasannya itu, Tiro menjadikan analisa sejarah dan hukum sebagai dasar pijakannya (Ali dkk, 2008).
Dua seting politik di atas penting sebagai cara membaca Aceh lebih utuh. Apalagi wajah Aceh tidak lagi sama setelah 41 tahun GAM dan 12 tahun kesepakatan damai di Helsinki. Perdamaian politik Helsinki itu telah menghentikan cita-cita kemerdekaan GAM dan berganti dengan jalan demokrasi.
Namun, ternyata, demokrasi memunculkan masalah berikutnya.
Ketika demokrasi hanya meniscayakan satu hal, yaitu, diskursif, ternyata tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh para mantan kombatan. Karena demokrasi menyediakan ruang deliberatif, meminjam frasa dari Habermas, yang memungkinkan setiap ide, gagasan melalui proses yang diskursif dan melewati uji publik (Hardiman 2009).
Demokrasi yang meniscayakan diskursif dan uji publik demikian, tidak dikenal dalam tradisi pergerakan politik Aceh Merdeka. Demokrasi jelas menghendaki ruang percakapan publik yang luas, tentu tidak efektif dalam masa perang. Sebab perang, harus dibangun dengan agitasi dan propaganda. Sehingga yang terjadi adalah mantan kombatan, yang sudah berpolitik itu, malah gagal memanfaatkan ruang politik yang terbuka lebar sejak tahun 2005.
Dalam keadaan demikianlah, kita kemudian dapat mulai memahami, mengapa gagasan etnonasionalisme, sebagai ide utama organisasi GAM, itu kalah dengan gagasan islamisme, yang merupakan ide utama di Aceh sejak zaman revolusi nasional. Padahal, kedua topik pernah itu menjadi perdebatan sengit di masa-masa awal reformasi, tentang apakah Aceh lebih menghendaki formalisasi hukum syariah atau keadilan (baca: merdeka).
Formalisasi hukum syariah sendiri merupakan gagasan yang lama mengendap setelah berakhirnya peristiwa Darul Islam Aceh, yang terus dicoba dalam berbagai kebijakan pelaksanaan hukum syariah. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Hasby Wahidy, yang pernah menjadi aktivis pemuda PUSA , dengan membentuk Biro Unsur-Unsur Syariat Islam di tahun, yang berujung pada pergantiannya oleh Pemerintah Pusat oleh Muzakkir Walad di tahun 1968 (Nashir, 2013). Namun, cara rezim Orde Baru menangani Aceh demikian, dalam pandangan Sjamsuddin (1989) telah membuat Beureuh kecewa. Lalu, karena sentimen itulah terjadi perjumpaan antara veteran Darul Islam dengan Hasan Tiro, yang lebih menjadikan isu pengelolaan kekayaan alam, sebagai bentuk ketidakadilan Pemerintah Pusat kepada Aceh, sebagai alasan untuk melakukan perlawanan kembali.
Namun, ketika Tiro mulai bergerak kepada gagasan etnonasionalisme, ide islamisme masih kuat mengendap di kepala elite politik dan intelektual Aceh. Kelompok bahkan bergerak dari tengah untuk mendorong agenda politiknya itu.
Oleh elite politik, hal itu ditunjukkan dengan mendukung penuh kepada PPP untuk mengalahkan dominasi Golkar. Dukungan kepada PPP dijadikan sebagai tempat pertujukan komitmen Aceh terhadap Islam (Ali, 1996). Sedangkan oleh golongan intelektual, yaitu para sarjana dari IAIN Ar Raniry, Darussalam, lebih mengisi ruang-ruang birokrasi, seperti menjadi pengajar di perguruan tinggi, bekerja di Kementerian Agama dan menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya gagasan-gagasan tentang Islam juga mendapatkan ruang diskursusnyanya di media Sinar Darussalam, sebuah majalah ilmiah yang terbit secara rutin sejak tahun 1969 sampai akhir tahun 1990-an.
Proses yang sistematis dari golongan elite politik dan intelektual tersebut, kemudian ikut menjelaskan mengapa setelah Aceh mendapatkan otonomi khusus di tahun 2001, untuk menjalankan Syariat Islam, maka produk hukum di bidang aqidah, ibadah, syiar Islam dan jinayah mampu dilahirkan dengan cepat.
Lalu, ketika ide islamisme bergerak dari tengah, di saat yang bersamaan, gagasan etnonasionalisme berada di pinggiran. Di saat pendukung gagasan islamisme menulis buku yang sistematis, mengadakan pengajaran dan seminar secara regular. Pendukung gagasan etnonasionalisme hanya mampu berpidato di tempat terpencil, mendengar ceramah dari kaset secara diam-diam, mencetak pamflet dan mengedarkan stensilan ceramah secara terbatas. Baru setelah rezim Orde Baru tumbang, ada peluang politik untuk membangun framing tentang etnonasioanalisme secara luas.
Ada euforia di sana-sini. Salah satunya dengan aksi-aksi kolosal, seperti referendum, mogok massal dan perayaan hari milad GAM secara terbuka. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Operasi militer dari pemerintah pusat berhasil membuat gagasan etnonasionalisme kembali ke pinggir. Bahkan setelah MoU Helsinki pun tidak mampu membawa gagasan itu kembali ke tengah, hatta mantan kombatan menduduki posisi politik yang strategis di Aceh.
Bahkan kini, produk hukum syariah lebih banyak lahir dan mendapat sambutan masyarakat, seperti Jinayah dan Hukum Acara Jinayah, Bank Syariah, Dinas Dayah dan keterlibatan ulama dalam memberi pertimbangan pada setiap kebijakan. Berbanding terbalik dengan produk hukum bercorak etnonasionalisme yang tidak mendapat dukungan penuh bahkan memunculkan riak-riak perlawanan, seperti kelembagaan Wali Nanggroe, bendera, lambang dan himne Aceh.
Perubahan sosial politik ini tentulah tidak ajeg. Namun bila ditelusuri secara genealogis, dapat dikatakan, bahwa gagasan islamisme dalam bentuk formalisasi hukum Islam di Aceh, telah memenangkan pertarungan narasi. Dan akan semakin kuat posisinya dalam membentuk identitas politik dan budaya di Aceh di kemudian hari.
* Makalah ini disampaikan pada diskusi Friday Forum IAIN Langsa, 2 Maret 2018
Gambar sebelum olah digital diambil dari : republika.co.id.