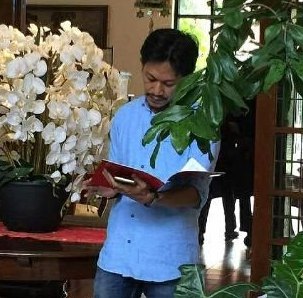Menuju Pilpres April 2019 mendatang, berbagai hal hal kontroversial seolah-olah timbul tenggelam dan menjadi asupan publik setiap hari. Berbagai polemik terus bermunculan setiap saat,dan menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi, publik figur, maupun masyarakat awam sekalipun. Salah satunya mengenai penggunaan istilah “kafir” yang menjadi polemik dipusaran Pilpres kali ini.
Nahdhatul ulama(NU) sebagai salah satu organisasi Islam massa terbesar di dunia, tempo lalu membuat heboh jagat maya. Pasalnya, NU secara resmi menganjurkan anggotanya untuk tidak lagi menggunakan sebutan istilah kafir terhadap non-Islam, karena menganggap penggunaan istilah tersebut terlihat ofensif dan cenderung mengambil konotasi yang buruk (menghina). Dalam rapat pleno Munas NU yang dilaksanakan di Banjar beberapa minggu yang lalu, organisasi itu menjelaskan penyebutan istilah kafir tidak dikenal dalam sistem negara bangsa. Karena dalam negara kebangsaan setiap warga negara dianggap sama dimata hukum (konstitusi), oleh karena itu, NU menganjurkan para anggotanya untuk menyebut non-muslim sebagai muwathin atau warga negara.
Berbagai reaksi muncul ditengah masyarakat, sebagian sepakat atas keputusan hasil munas NU tersebut. Keputusan itu dinilai sejalan dengan asas bangsa Indonesia, yang menghargai keberagaman beragama. Apalagi, Indonesia negara yang berdasarkan pada falsafah Pancasila bukan formalisasi Islam. Keputusan NU tersebut juga menemukan momentumnya beberapa tahun belakangan ini, yaitu ketika ujaran kebencian berbau agama telah menjadi suatu momok yang memperihatinkankan dalam wacana politik di tanah air.
Pun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim yang menolak keputusan NU tersebut. Pihak yang menolak membangun argumen bahwa apa yang dilakukan oleh “organisasi sarungan” itu telah menyalahi aturan kaidah dalam agama Islam karena berusaha mengamandemen al-Quran dan menghilangkan kata kafir. — satu istilah kafir yang tertera di dalam ayat al-Quran. Bahkan salah satu surat dalam al-Qur’an bernama surat al-Kafirun (orang-orang kafir). Di sisi lain, sebagian masyarakat juga menilai adanya kepentingan terkait kontestasi politik, lantaran NU dianggap pro petahana. Keputusan NU itu dianggap bertujuan untuk menggalang suara dari pemilih non-muslim, pada Pemilu 2019.Tudingan bahwa NU pro petahana bukan tanpa alasan, pasalnya, Joko Widodo pada ajang Pilpres 2019 ini menggaet Ma’ruf Amin yang menjabat sebagai rais aam PBNU, sebagai pendampingnya.
Ketua konferensi Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan, penggunaan istilah kafir mengandung “kekerasan teologis” dan sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai alat mendiskriminasi kaum minoritas (non-muslim). Dia juga menegaskan bahwa NU tidak bermaksud untuk mengubah makna dan istilah kafir dalam al-Qur’an.
Tidak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya ekstremisme Islam – oleh golongan tertentu, penggunaan istilah kafir tidak lagi pada konteksnya. Malah menjadi semacam suatu batasan penutup dan alat untuk mengintimidasi dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan heterogen. Kata “kafir” dengan mudah mengalir dari mulut kemulut untuk ditujukan kepada mereka yang dianggap tidak sepemahaman dan yang berbeda pendapat.
Ditambah, ini adalah tahun-tahun dimana dunia politik yang paling kacau, pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Terjadinya berbagai perubahahan tatanan arah perpolitikan di Indonesia, mulai dari munculnya berbagai partai-partai politik baru, yang mengusung berbagai ideologi. Selain itu berbagai kebijakan mulai disusun secara lebih sistematik sesuai alur demokrasi. Kebebasan berpendapat di ruang publik terbuka. Namun, tampaknya kebebasan tersebut, member ruang pula untuk tumbuh pesatnya perkembangan ormas ormas Islam ekstrim, seperti HTI maupun FPI,yang beberapa tahun terakhir ini mulai menunjukan sikap yang radikal terhadap sistem yang ada. Hal yang tidak akan kita temukan di zaman Orde Baru. Di mana ormas maupun parpol yang yang tidak sejalan dengan pemerintah cenderung dibungkam dan kehilangan eksistensinya sama sekali. Berkembangnya paham radikal golongan islam konservatif menjadi sesuatu yang amat mengkhawatirkan terhadap kedaulatan NKRI dikarenakan mereka berusaha meraungkan paham khilafah yang notabene bertentangan dengan konstitusi maupun sistem negara Indonesia.
Hal ini pula yang menjadi perhatian serius para kyai NU,yang dalam pandangan mereka Pancasila merupakan suatu landasan final dan tidak dapat diganggu gugat. NU yang merupakan ormas yang lahir tahun 1920 ini punya pandangan yang lebih moderat, terbuka dan pluralisBahkan sering dicap liberal oleh kelompok ormas ekstrim lainnya.
Hal yang harus direnungkan, dalam cara kita bernegara adalah bahwa perbedaan pendapat dalam suatu negara demokrasi merupakan hal yang lumrah dan lazim . Malahan hal itulah yang menjadi ciri khas dalam sistem demokrasi, sebagai perwujudan kebebasan beraspirasi baik secara individual, kelompok serta golongan dalam masyarakat yang plural. Sehingga tidak mengherankan munculnya pro-kontra bahkan konflik dalam masyarakat sekalipun, yaitu manakala suatu masalah dilihat dari persepsi dan sudut pandang yang berbeda,yang diiringi dengan sikap tidak toleran. Perihal benar atau salahnya adalah kembali kepada tingkat kemampuan individu meninjau permasalahan sesuai konteks dan konsep yang diterapkan.
Alhasil terlepas dari berbagai stigma yang bermunculan, patutlah kita sadari, bahwa intisari serta tujuan dalam merumuskan persoalan polemik istilah kafir tersebut, apalagi dalam subtansi keagamaan yang relatif sensitif, tentu perlu pengkajian yang lebih serius dan matang. Melalui pembacaan referensi keagamaan yang disandingkan dengan konsepsi Pancasila sebagai ideologi yang final di negeri ini.
-Sahirdin*-

Disclaimer: Pendapat dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mesti mewakili pendapat atau pandangan padébooks.com