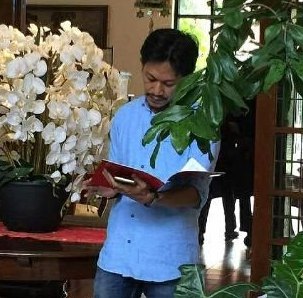PENDAHULUAN
Mencermati perkembangan yang terjadi di Islam Indonesia sepanjang tahun 2016, terutama beberapa peristiwa yang terkait dengan persoalan soisal-politik-keagamaan, penulis menjadi kembali ingin membaca tulisan Martin Van Bruinessen yang memunculkan istilah conservative turn in Indonesia. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Martin melalui istilah itu. Apakah ia ingin mengatakan bahwa pemahaman keagamaan Muslim Indonesia sebelumnya adalah konservatif, lalu berevolusi dan keluar dari konservatisme itu dan kini konservatisme itu terulang kembali? Istilah conservative turn yang pertama sekali digunakan oleh Martin tahun 2013 dalam asumsi penulis menjadi suatu prediksi akademik yang terbukti kebenarannya hari ini, meski dalam pemahaman penulis conservative turn yang dimaksudkan Martin adalah adanya sejumlah gejala bahwa pemahaman Muslim terhadap agamanya semakin menguat, kalau tidak ingin dikatakan mengarah kepada kekerasan berjamaah (communal violence) dengan mengatasnamakan agama mengutip istilah Duncan. Kasus-kasus di mana pemahaman keagamaan Muslim, terutama konservatisme mereka membaca teks-teks suci terbuka untuk ditunggangi oleh aktivitas politik. Tulisan ini dibagi atas dua pembahasan. Pertama, tentang hasil penelitian lembaga riset dan sejumlah pakar tentang Islam Indonesia dengan perdebatan seputar kecenderungan ke arah konservatisme, sebagai the outsider’s perspective. Kedua, mengenai konservatisme Islam sebagai tunggangan politik: pengalaman Tunisia.
HASIL RISET TENTANG ISLAM INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2010-2014
Freedom House menggambarkan perubahan Indonesia sebagai “model dari integrasi yang sukses antara demokrasi dan Islam” menjadi negara dengan “merosotnya pluralisme” akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak satu dasawarsa lalu. Penilaian lain atas kondisi Muslim di Indonesia kontemporer kerap juga diungkapkan sebagai meningkatnya “political Islam”, “radical Islam”, atau “Islamist political violence”.
Martin Van Bruinessen, tahun 2011 menulis artikel di salah satu jurnal ilmiah RSIS Singapura. Dalam tulisan itu, terlihat kecemasan dan kegelisahan Martin terhadap perubahan umat Islam Indonesia yang terbesar di dunia secara kuantititatif, terutama pasca Orde Baru. Ia menulis judul: “What happened to the smiling face of Indonesian Islam?”. Ia menilai Islam Indonesia yang ia kenal melalui studinya sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1980-an yang selalu menampakkan wajah yang manis, penuh senyuman (the smiling face), mulai berubah menyeramkan, tidak enak dipandang dll. Era ini melahirkan Cak Nur dan Gusdur sebagai representasi tokoh Islam paling brilian. Namun berakhirnya masa orde baru, mereka mulai kehilangan “power” dalam debat-debat publik dengan munculnya Islam radikal dengan tampilan yang lebih kuat.
Tahun 2013, ISAS Singapura merilis hasil studi lapangan Martin dkk sepanjang tahun 2007-2008 dengan judul: “Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn”. Dalam buku ini, Martin dan Baqir masih meyakini adanya wajah non-konservatif Islam di Indonesia. Namun posisi saya setelah menyimpulkan tulisan Martin dan Baqir justru menegaskan bahwa konservatisme Muslim di Indonesia semakin mengkristal, menguat, membaja. Conservative turn dalam bahasa mereka hanya masih sebatas kecenderungan.
Beberapa catatan Martin dalam buku Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Conservative Turn bahwa (1) Demokratisasi politik telah menarik banyak orang yang sebelumnya terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga yang mendukung perdebatan intelektual ke dalam karier di partai politik atau institusi, sehingga melemahkan landasan sosial bagi wacana Islam liberal dan progresif, (2) Asumsi bahwa mayoritas itu bersifat konservatif atau cenderung berpandangan fundamentalis tidak bisa diyakini begitu saja, (3) Pemikiran Islam liberal hanya bisa berkembang apabila dilindungi oleh rezim otoriter, (4) Conservative turn di Indonesia sebagian disebabkan adanya pengaruh dari Timur Tengah, khususnya Semenanjung Arab, dalam bentuk kembalinya para lulusan dari perguruan tinggi di Arab Saudi, institut pendidikan yang didanai Arab Saudi dan Kuwait untuk mensponsori penerjemahan sejumlah teks “fundamentalis”, dukungan ideologis dan keuangan untuk gerakan Islam lintas negara, (5) Menonjolnya keturunan Arab yang memegang kepemimpinan gerakan radikal tampaknya mengarah kepada peran mereka sebagai perantara proses Arabisasi Islam Indonesia. Tak bisa disangkal, pelaku keturunan Arab dan dana Arab memang meningkat, tetapi pengaruh mereka tidak secara khusus bekerja dalam arah anti-liberal maupun fundamentalis.
Istilah conservative turn di Indonesia juga digunakan oleh Hamayotsu (2014) dalam bukunya Conservative Turn? Religion, State and Conflict in Indonesia. Dia mengatakan bahwa ketika ada konflik yang melibatkan etnis dan identitas lainnya, maka yang yang menjadi pemicunya itu adalah bukan persoalan etnis dan identitas lain tersebut, tapi kompetisi politik antar elit terkait pembagiaan sumber-sumber kekayaan negara dan tanah (political competition among elites over distribution of state resources, land. Ethnicity and other identities were not the primary cause of the conflict)”
Berbeda dengan Hamayotsu, Duncan mengatakan bahwa…”the essential source and character of the communal violence is religion..” (agama adalah sumber penting dan karakter kekerasaan komunal). Berdasarkan observasi dan interview lebih dari 17 tahun pada internal masyarakat yang dibuang dan terdampak kekerasan, ia menyimpulkan bahwa the communal violence diakibatkan oleh kompetisi politik antar elite terhadap pembagian sumber-sumber kekayaan negara dan tidak ada kaitannya dengan agama. Oleh mereka, agama dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan yang kemudian menjadi pemicu kekerasan (political competition among elites over distribution of state resources, land and other religious issues). Kemudian dia menyimpulkan bahwa agama sebagai identitas bersama dan klaim, lebih mendapatkan ciri khas bagi orang-orang yang terlibat dalam konflik (…religion as a collective identity and claim has gained more salience among participants in the conflict…). Duncan menyimpulkan bahwa…”the essential source and character of the communal violence is religion..” (agama adalah sumber penting dan karakter kekerasaan komunal). Kesimpulan Duncan ini perlu diperhalus lagi untuk mengatakan bahwa bukan agama yang sebagai ajaran itu yang menjadi pemicu kekerasan komunal itu. Lalu apa kaitan antara konservatisme dengan kekerasan komunal?
Sebenarnya, kecenderungan konservatisme tidak selalu negatif, karena masyarakat muslim membutuhkan itu untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, jika kecenderungan konservatisme itu menjadi opini publik, ini sangat mengkhwatirkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syarafi (2011), bahwa menghadapi opini publik yang dikuasai kekuatan konservatif itu jauh lebih sulit dari pada menghadapi kekuatan politik yang despotik. Despotisme juga bisa lahir dari konservatisme yang mendapat sokongan politik. Menguatnya konservatisme di Indonesia bisa jadi seperti yang dikatakan Baqir (2013) bahwa ketika pemerintah tampak seperti tidak peduli untuk menjaga batas-batas wacana publik, beberapa varian kelompok konservatif itu seperti mendominasi. Karenanya, tidak selalu negatif jika dalam tulisan ini penulis merekomendasikan untuk penguatan pemerintah untuk mengontrol conservative turn dalam wacana publik.
KONSERVATISME ISLAM SEBAGAI TUNGGANGAN POLITIK: PENGALAMAN TUNISIA
Beberapa kasus di Indonesia, sekilas mirip dengan dalam sejarah Tunisia modern, di mana konservatisme Islam ditunggangi oleh politik. Haddad dan Bourguiba adalah contoh di mana politik menunggangi konservatisme di Tunisia. Haddad yang oleh Tha’alibi diberi signal untuk meneruskan kepemimpinan dalam partai harus menghadapi tragedi “penggulingan” agar ia tidak mewarisi kepemimpinan pendahulunya Tha’alibi. Berawal dari pergumulan dalam tubuh partai, kemudian dipolitisasi menjadi provokasi berbalut isu penistaan agama melalui masterpiece Tahir Haddad dalam bidang sosial-keagamaan, yaitu Imra’atuna fi al-Syari’ah wa al-Mujtama’. Ibn Milad (1991) menggarisbawahi peristiwa itu dengan sebuah ungkapan: Siyasatun qabla an-takuna diniyyatan. Berawal dari persoalan politik kemudian melebar menjadi persoalan keagamaan.
Haddad terjun langsung dalam gerakan kebangsaan sejak awal berdirinya partai al-Dustur pada saat statusnya masih sebagai pencari ilmu di Jami’ Zaytuna. Dia aktif dalam surat kabar milik partai. Dia banyak menulis di situ. Dia juga mendirikan organisasi yang diberi namaiMuqawamah al-Bida’ wa al-Israf di bawah pimpinan Husayn al-Jaziriy (pemilik surat kabar al-Nadim) yang didirikan dengan misi perlawanan terhadap zawiyah dan tarekat sufi, serta life-style sebagian besar masyarakat Muslim Tunisia yang dikenal boros saat itu. Pada saat ia ingin mendirikan serikat buruh/pekerja (al-niqabat al-‘ummaliyyah), dengan keyakinan bahwa pendirian serikat ini akan dapat membuka jalan bagi kemerdekaan buruh, dan mengajukan proposal kepada partai untuk bersedia mendanai serikat tersebut, namun niat dan usaha dan permintaannya tersebut tidak dikabulkan oleh pengurus partai lainnya. Pasca penolakan itu, Haddad mengurangi aktivitasnya di kepartaian. Ia bersama-sama dengan Muhammad al-Dar’i memberitakan ke publik bahwa partai tidak berkeinginan mendukung serikat buruh. Haddad lalu dinilai telah memecah-belah internal-partai dan merusak perjuangan partai. Di tempat lain, lajnah tanfidziyyah partai juga masih menyimpan konflik dengan Haddad. Maka saat Haddad meluncurkan bukunya Imra’atuna fi al-Syari’ah wa al-Mujtama’, kalangan partai yang tidak bersimpati dengan Haddad semakin melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Haddad sebagai kader partai, meski dalam buku tersebut terdapat pemikiran-pemikiran progresif dan berani, jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan dalam tema yang sama pada periode ini.
Kalangan partai kemudian memanfaatkan pemikiran-pemikiran Haddad ini sebagai jalan untuk merusak ketokohan Haddad. Prahara pun terjadi, sebab partai akhirnya mengeksploitasi isu ini menjadi isu keagamaan di masa itu. Konflik yang terjadi antara Haddad dan orang-orang di internal partai digiring kepada persoalan agama untuk menutupi akar konflik sebenarnya. Konflik politik internal partai bermetamorfosa menjadi konflik keagamaan, syariah, hukum Islam. Karya Haddad kemudian diserang oleh banyak sekali penulis saat itu, di antaranya adalah Syaikh Raji Ibrahim, anggota lajnah tanfidziyyah, bukan cuma itu, masyayikh Zaytuna juga turut meramaikan pergumulan ini. Mereka mengkitik, menerbitkan sejumlah karya yang meng-counter pikiran-pikiran Haddad. Pimpinan tertinggi Jami’ Zaytuna juga mengeluarkan rekomendasi untuk “membredel” karya Haddad sekaligus mencabut gelar akademik yang pernah diraihnya dari Jami’ Zaytuna. Anehnya, pasca pecahnya partai pada tahun 1934, tokoh-tokoh partai kubu al-diwan al-siyasiy mengklaim bahwa Haddad adalah bagian dari mereka yang mereka dukung serta mereka anggap sebagai “tumbal” politik lajnah tanfidziyyah.
Pasca kepemimpinan Tha’alibiy, al-Hurr al-Dusturiy menciptakan dua sayap di internal partai. Sayap pertama dimotori oleh Bourguiba yang menguasai al-diwan al-siyasi atau Bourgibiyyun di mana ke-Tunisan (al-huwiyyah al-tunisiyyah) sebagai ideologinya yang tidak pro-Timur atau pro-Barat (la syarqiyyatan wa la gharbiyyah). Dan sayap kedua, Salih Bin Yusuf yang memotori al-amanah al-‘ammah atau Yusfiyyun yang menggunakan kekuatan Arab-Islam sebagai ideologinya, menimbulkan ketegangan di internal partai. Pergolakan politik ini mendesak Bourguiba menentukan pilihan politik liberal-sekular. Pada saat yang sama, Bin Yusuf bergabung dengan kekuatan Islam tradisionalis dan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan nasionalisme Arab dan Timur Tengah. Pedagang dan petani kaya yang berasal dari dua wilayah Sfax dan Jerba juga berada di belakang dan mendukung keputusan politik Bin Yusuf, termasuk juga masyarakat dari Selatan Tunisia. Bin Yusuf juga tercatat menghadiri KTT Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Di sini ia mempertegas posisi politiknya dan aliansinya dengan Jamal ‘Abd al-Nasir Presiden Mesir saat itu. KKT Bandung ini mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang kontra terhadap Barat. Di tahun yang sama, pada tanggal 14 Oktober, Bourguiba menghadiri pertemuan di Kairo. Pertemuan itu mempertegas posisi politik Bourguiba untuk berafiliasi kepada Barat. Pertemuan Kairo ini melahirkan sejumlah keputusan diantaranya yang paling penting adalah sayap al-diwan al-siyasiy pimpinan Bourguiba menarik dukungan dan memisahkan diri dari partai al-hurr al-dusturiy. Konflik dengan Bin Yusuf dan al-Yusfiyyun mendorong Bourguiba mempercepat dan meneguhkan aliansinya dengan Perancis, bukan saja dalam masalah politik, tapi juga dalam masalah budaya. Karenanya, pasca konflik itu, Bourguiba melakukan sterilisasi sebanyak mungkin terhadap pengaruh Arab-Islam.
Ketegangan politik antara Bourguiba dan Bin Yusuf juga memantik sentimen konservatisme di Tunisia. Saat Majallat al-Ahwal al-Sykhshiyyah (MAS) dirilis tahun 1956 yang merupakan produk undang-undang pertama masa pemerintahan Bourguiba dalam masalah hukum keluarga, Salih Bin Yusuf, menurut catatan Kenneth J. Perkins, yang menjadi rival politik Bourguiba, menuduhnya melakukan pengharaman terhadap sesuatu yang dihalalkan Tuhan dan sebaliknya, terutama dalam pasal 18 tentang pelarangan poligami MAS 1956. Menurut keterangan Mastiri, ketegangan antara Bourguiba dan Bin Yusuf berawal dari persoalan politik di internal partai al-hurr al-dusturiy. Keduanya berkompetisi untuk merebut kekuasaan sebagai ketua partai pada permulaan tahun 1954. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Salih Bin Yusuf tidak menerima menjadi orang nomor dua di Republik Tunisia. Secara kepartaian, Bin Yusuf merupakan al-amin al-‘amm dan Bourguiba sebagai ketua al-diwan al-siyasi yang mengeksekusi program kerja partai. Selain itu, keduanya juga bersitegang dalam hal kesepakatan kemerdekaan dalam negeri Tunisia. Pasca Bourguiba menjadi presiden, kompetisi itu berlanjut menjadi serangan-serangan terhadap pemerintahan Bourguiba (al-tanafus alladzi tahawwala ila shira’ a’a al-hukm).
Kelompok salafi juga memanfaatkan isu agama untuk menyerang Bourguiba yang mereka cap sebagai pemimpin yang mengganti wajah Tunisia yang dahulu merupakan sebuah negara Islam menjadi negara sekular-kafir jika dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Meski konstitusi Tunisia tahun 1959 dalam Bab I tentang Aturan Umum Pasal 1 dengan tegas menyebut bahwa Tunisia merupakan negara Islam di mana bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara, dan republic sebagai sistem pemerintahannya (tunis dawlatun mustaqillatun, dzatu siyadatin, al-islamu dinuha, wa al-‘arabiyyatu lughatuha, wa al-jumhuriyyatu nizamuha), namun terlihat bahwa kelompok salafi belum merasa puas sebab pasal satu konstitusi Tunisia tahun 1959 tidak menyebut syariat Islam sebagai landasan konstitusi dan sistem pemerintahannya. Bagi Bourguiba, sebagaimana pidato yang disampaikannya tertanggal 23 Februari 1965, bahwa Islam adalah sebagai perekat kuat yang menyatukan seluruh elemen umat, menjadikannya seperti satu tubuh meski mereka berbeda. Bourguiba menunjukkan bahwa ia mampu menyatukan masyarakat dengan meunifikasi hukum dan peradilan dalam satu undang-undang dan peradilan di mana warga negara dari suku, agama, ras, dan agama apa pun tunduk pada pada aturan di dalamnya. Pernyataan Bourguiba ini senafas dengan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Menurut penulis, Bourguiba berhasil memenangkan perdebatan sekitar sistem pemerintahan yang tercantum dalam konstitusi Tunisia tahun 1959 Bab I tentang Aturan Umum Pasal 1 untuk sebuah negara baru pasca kemerdekaannya. Fadhil ibn ‘Asyur secara resmi pernah menyusun draf rancangan konstitusi negara baru Tunisia. Dalam draf tersebut disebutkan bahwa Tunisia merupakan negara Islam dengan menerapkan manhaj Islam atau syariat Islam dalam pemerintahannya. Namun, faktanya meski mereka sepakat bahwa Islam adalah agama resmi negara Tunisia, namun syariat Islam tak pernah ada dalam konstitusi Tunisia tahun 1959 itu.
Di level global, Bourguiba difatwakan kafir dan murtad oleh Syaikh Bin Baz. Luthfi Hajji mengutip fatwa Bin Baz tahun 1401 H yang berjudul: al-radd ‘ala al-ra’is Abi Bourguiba (hakadza) fi-ma nusiba ilayhi min dzalik. Selain memfatwakan kafir dan murtad terhadap Bourguiba, Bin Baz juga menyerukan kepada seluruh pemimpin di negara-negara Muslim untuk memutuskan hubungan diplomatik-politik dengan Bourguiba sampai Bourguiba mau bertaubat atas pandangannya yang melarang poligami dan kesetaraan dalam pembagian waris.
Meski banyak kritik terhadap relasi Bourguiba dan Islam, namun pembelaan terhadap Bourguiba selalu disuarakan oleh masyarakat dan ulama Tunisia. Ketika banyak orang yang menyalahkan Bourguiba karena pidatonya tentang kebolehan berbuka bagi bagi sejumlah profesi di Tunisia, sejumlah Imam di Bizerte justeru mengeluarkan keputusan bersama untuk mendukung Bourguiba. Ahmad al-Mastiri menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap sejarah pemerintahan Bourguiba bagi generasi hari ini. lembaran-lembaran kelam tentang sejarah Bourguiba banyak ditulis di masa presiden selanjutnya, dan semakin menguat terutama pada tahun 2000 pasca wafatnya Bourguiba. Sejumlah tulisan itu hanya memuat sisi gelap dari kehidupan Bourguiba tanpa menampilkan sisi positif dari seorang Presiden pertama Tunisia tersebut dengan target generasi baru Tunisia. Muhsin Marzuq (Ketua Organisasi Arab Demokrat) mengatakan bahwa Bourguiba adalah seorang Muslim moderat-reformis. Ini menyangkal pernyataan yang mengatakan bahwa Bourguiba adalah sekularis, berseberangan dengan agama. Bagi Amal Musa, Bourguiba bukanlah seorang kafir, dia juga bukan seorang ateis. Bourguiba menurut Musa, melihat Islam sebagai agama yang harus memiliki pemahaman kontemporer tanpa melepaskan turath. Umat harus memiliki pemahaman baru terkait dengan hubungan antar manusia di era modern.
KESIMPULAN
Peristiwa sejarah di Tunisia, paling tidak dapat menggambarkan kepada masyarakat di Indonesia, betapa sebenarnya politik itu sangat mungkin sekali menunggangi konservatisme Muslim Indonesia. Membersihkan politik untuk tidak menunggangi konservatisme Islam bukanlah persoalan mudah. Namun, jika itu dapat dilakukan, tidak tertutup kemungkinan munculnya kembali wajah ramah Islam Indonesia. Semoga. Wallahu a’lam bi al-shawab.
– Budi Juliandi –
* Makalah ini disampaikan pada diskusi Friday Forum IAIN Langsa, 23 Februari 2018

Disclaimer: Pendapat dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mesti mewakili pendapat atau pandangan padébooks.com
Sumber gambar tajuk sebelum olah digital: flickr USArmyAfrica, lisensi CC By 2.0