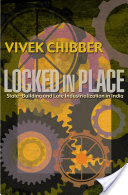 Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India
Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India
History
Princeton University Press
2006
360
Buku Locked in Place: State Building and Late Industrialization in India (Princeton University Press, 2006) merupakan studi ilmu politik pasca colonial India. Menariknya, si penulis, Vivek Chibber membandingkan masa pemerintahan Jawaharlal Nehru Perdana Menteri pertama di India dengan rejim Park Chung-hee, di Korea Selatan. Korea menekankan pada kebijakan ELI (Export Led Institution), sebaliknya India menggunakan kebijakan ISI (Import Substitution Industrialization).
Penekanan pada ELI di Korea Selatan berhasil karena campur tangan pemerintah dalam mendisiplinkan bisnis-bisnis besar. Keberhasilan ELI jelas didukung dengan kualitas birokrasi yang bagus dan Negara yang kuat. Korea mempunyai rasionalitas birokrasi yang koheren dimana Negara bekerja sama dengan asosiasi industry mobil, sepatu, listrik, elektronik. Tangan Negara yang kuat dengan penciptaan bank-bank pemerintah merupakan upaya awal Negara dalam menciptakan kredit kepada pengusaha lokal. Nasionalisasi bank di Korea tahun 1960 an bertujuan untuk mencegah rent seeker (pengusaha yang melobi ke pemerintah/ kongres) dan mengontrol dunia finance. Tujuan dari nasionalisasi bank adalah untuk mengontrol belanja tahunan dan mengontrol arus finansial dan arus kredit industri di bawah pengawasan menteri keuangan. Berbeda dengan India, untuk memulai proyek-proyek industri, businessman tidak perlu mendapatkan ijin dari menteri keuangan dan parlemen, mereka hanya memerlukan ijin dari nodal agency atau komite dagang yang dibuat oleh pemerintah dan menteri keuangan sebagai penanggung jawab implementasi dari nodal agency. Komite dagang mempunyai kekuatan utama untuk menyediakan kredit dan pembelanjaan. Menteri keuangan tidak bisa menganulir kebijakan-kebijakan kamar dagang. Pemerintah mempunyai legitimasi untuk mengontrol modal dan menghukum bisnis yang tidak sejalan dengan agenda pembangunan. Berbeda dengan Park Chung-hee, Nehru tidak mempunyai keterlibatan langsung dengan kamar dagang. Ia bahkan tidak mempunyai kuasa penuh terhadap kongres.
Sebaliknya dari Korea Selatan, di India, tidak ada kerjasama yang koheren antara agen pemerintah dengan asosiasi-asosiasi perdagangan. Sifat red tape bureaucracy (regulasi birokrasi yang berlebihan) India di bawah Nehru yang sosialis malah acak adut mendisiplinkan pengusaha-pengusaha besar dan berakhir dengan menekankan kebijakan ISI. National congress di bawah Nehru kacau balau. Negara memberi subsidi kepada firma-firma, tapi banyak firma susah dikendalikan. India menggunakan kebijakan impor yang justru menyebabkan protes besar di tingkatan pemilik modal lokal dan para buruh yang ditekan upahnya. Hal ini berbeda dengan kebijakan ekspor di Korea yang mendapatkan dukungan penuh oleh pihak pemilik modal lokal yang sebagian besar bergerak di sektor manufaktur. Korea menyadari bahwa penekanan ekspor harus menjadi hasrat kelas pengusaha bukan hasrat negara, sebaliknya, kebijakan impor cenderung menjadi hasrat Negara. Sebaliknya India di bawah Nehru melalui proyek sosialisme “Bombay Plan” (BP) nya gagal untuk menekan kelas pengusaha. Para birokrat tetap mempertahankan elit-elit lamanya. Elit birokrat cenderung benci pengusaha dan menekannya. Bombay Plan menasionalisasi semua perusahaan dan menekan pajak yang tinggi kepada klas pengusaha. BP juga mengontrol upah minimum buruh dan training-training buruh. Industri Negara menguasai sektor-sektor yang berkenaan dengan sistem pertahanan, infrastruktur, seperti rel kereta api sampai proyek energi atom. Miskinnya investasi diperburuk dengan ketidaksambungan antara pihak kongres dan menteri-menteri di bawah Nehru. Masing-masing punya kepentingan. Pihak kamar dagang India kebingungan hendak mengajukan lobi ke menteri atau ke kongres. Kamar dagang terus berseteru dengan menteri keuangan soal kebijakan investasi. Sedangkan menteri-menteri menciptakan sel-sel kekuasaannya tersendiri. Ketidakkoherenan antar instansi ini diperburuk dengan berganti-gantinya kebijakan di setiap rencana pembangunan lima tahunan. Konsul-konsul pembangunan didominasi oleh aparatus birokrasi yang gagal untuk melobi target investasi. Tidak seperti di Korea Selatan, birokrasi India tidak mempunyai pendisiplinan yang efektif terhadap bisnismen yang secara mudah memonopoli sektor-sektor bisnis. Tidak ada tekanan secara langsung. Setelah mendapatkan lisensi investasi, pihak businessmen tinggal menjalankan operasinya. Bisnismen yang menjalankan investasinya dipastikan adalah segelontor elit yang mempunyai kedekatan dengan para birokrat pemberi ijin usaha. Hal ini tentu mematikan usaha-usaha kecil yang tidak mampu berkembang dikarenakan kerumitan birokrasi.
Di ranah agrikultur, ELI berhasil melakukan penguatan produksi agrikultur. Pemerintah Korea melakukan reformasi agraria, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Reformasi agraria tentu saja sangat penting karena dapat mencegah impor bahan kebutuhan pokok. Tentu saja harus diakui bahwa reformasi agrarian ini juga tidak lepas dari desakan Amerika Serikat untuk mencegah menjalarnya ketidakpuasan petani yang berujung pada tumbuh suburnya ideologi sosialisme. Penguatan produksi agrikultur juga sangat signifikan untuk mencegah inflasi mata uang karena impor bahan pangan dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang. Selain itu, harga kebutuhan pokok dapat ditekan. Park juga sadar bahwa stabilisasi pangan adalah stabilisasi upah karena upah buruh pasti mengacu pada hal yang paling mendasar yakni konsumsi bahan pangan.
Negara yang kita lihat sangat kapitalistis, seperti Korea Selatan, bahkan Taiwan, berhasil menjalankan program-program yang esensinya merupakan agenda Negara sosialis, seperti reformasi agraria. Sebaliknya, Negara-negara yang menjalankan program sosialisme di tahun 1960an, seperti India, termasuk juga Indonesia, berakhir dengan program “developmentalisme” yang dijalankan secara masif.
India tidak mempunyai state managerial yang bagus dan tidak mempunyai asosiasi sektoral yang memonitor kebijakan-kebijakan ekonomi seperti di Korea Selatan. Di bawah Nehru, kapitalisme tidak dapat dibungkam karena Negara tidak demikian kuat. Sementara di bawah Park Chung-hee di Korea Selatan, kapitalisme dapat berkembang dengan baik justru karena adanya negara yang kuat. Namun demikian, saya tidak mengatakan bahwa campur tangan negara perlu dihilangkan, kasus India dan Korea Selatan justru sekaligus menunjukkan gagalnya pasar sebagai sistem “self regulatory” karena ketika tidak dikekang oleh Negara, harga-harga komoditas menjadi naik tinggi, sebagai misal harga gula dan harga tekstil di India yang melonjak di akhir tahun 1940an. Gagalnya pasar untuk mengatur dirinya sendiri menyebabkan kaum industrialis mengandalkan peran Negara, yang ironinya ternyata berjalan dengan sistem birokrasi kacau balau.
Buku Vivek Chibber ini merefleksikan dua hal besar. Pertama, mengajak kita beranjak dari debat lama soal pelemahan Negara dan penguatan pihak pengusaha swasta. Korea Selatan menunjukkan bahwa salah satu syarat dari pertumbuhan eksport led industrialization adalah karena rasionalitas birokrasi dimana terjadi koherensi antara kerjasama menteri-menteri dengan pihak pemilik industri. Dengan demikian, untuk melakukan pembukaan investasi, justru dibutuhkan negara yang kuat, khususnya secara hukum dan koherensi antar birokrasi. Pertumbuhan ekonomi jelas merupakan kebijakan memerlukan Negara yang kuat, bukan sebaliknya . Intervensi negara jelas diperlukan untuk mencegah instabilitas pasar, naik nilai tukar mata uang, menciptakan tingkat upah yang stabil, meregulasi arus modal yang masuk dan mendisiplinkan kapital. Negara, seperti Korea, tidak berperan sebagai pemberi subsidi (seperti yang selama ini dilakukan oleh Indonesia) yang menyebabkan jatuh terjebak ke dalam hutang. Kedua, buku ini sekaligus merefleksikan kondisi pasca ideologi. Negara yang selama ini kita anggap menjalankan sistem kapitalisme mutakhir, seperti Korea Selatan, Taiwan dan Jepang, justru sangatlah sosialis. Parameternya pada pembagian tanah secara merata pada penggarap. Sebaliknya, negara yang dulunya menjalankan program sosialisme justru menyerah dengan menjalankan berbagai macam program pembangunan (developmentalisme) dan menjadi sasaran empuk berbagai proyek politik neoliberalisme.
Namun demikian, di buku ini, Chibber tidak menggambarkan skala politik regional. Mengapa India cenderung gagal? Mengapa Korea Selatan justru sukses?
Yang patut diperhatikan adalah pada negara-negara disekitarnya sebagai penunjang kerjasama. Secara regional, kasus India karena tidak ada negara-negara pendukung industri yang kuat. India dikelilingi oleh Bangladesh, Srilanka, dan Pakistan. Bandingkan dengan Korea yang disekitarnya didukung oleh Taiwan dan Jepang. Kondisi regional jelas terhubung dengan konteks waktu. Tahun 1960an, Amerika memaksa Korea untuk lebih menerapkan ekspor karena pada saat yang Amerika membutuhkan ekspor tekstil dalam jumlah besar. Hal paling terpenting adalah aliansi Jepang dan Korea. Amerika melakukan proteksi ketat terhadap ekspor dari Jepang. Namun Jepang menanamkan investasi industry offshore ke Korea yang nantinya di ekspor Amerika. Jepang memperbaharui mesin-mesin tekstil di Korea yang sudah menua demi meningkatkan kualitas ekspor. Di bawah rejim Park Chung-hee, kurang lebih terdapat 15 firma Jepang di Korea yang sampai 86% mendominasi ekspor ke Amerika. Tentu saja Park Chung Hee gembira karena ia juga mendapatkan pajak dari firma-firma Jepang tersebut.
– Hatib Abdul Kadir* –

Disclaimer: Pendapat dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mesti mewakili pendapat atau pandangan padébooks.com




