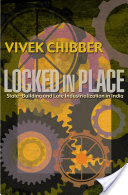Pada penghujung Agustus 2017 konflik di Arakan State1), Myanmar kembali terulang. Konflik ini mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar semakin meningkat. Rohingya yang merupakan etnis minoritas dan banyak bermukim di Arakan State, paling merasakan dampak dari konflik ini. Tercatat sejak konflik pecah pada Agustus, lebih dari 90.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh2).
Pemberitaan krisis kemanusiaan ini menjadi headline pemberitaan dunia dan Indonesia. Dari pemberitaan media, pemerintah Myanmar tidak berupaya melindungi etnis Rohingya dalam konflik ini3). Bahkan pemerintahan Myanmar terkesan membiarkan upaya genosida yang dilakukan militer terhadap etnis Rohingya. Krisis ini kemudian menarik simpati besar warga dunia. Kecaman dan juga ucapan duka membanjiri lini masa sosial media dan juga pemberitaan dunia. Tidak sedikit yang berusaha untuk memberi analisa mengenai krisis kemanusiaan di Arakan State.
Ada 2 cara pandang mainstream masyarakat Indonesia dalam melihat krisis ini. Pertama, masyarakat yang melihat krisis terjadi karena adanya konflik antar agama antara Budha sebagai agama mayoritas dan Islam sebagai minoritas4). Sebagian lain melihat politik penguasaan Migas di Arakan State yang melatar belakangi krisis di Arakan State5). Dalam pandangan penulis 2 cara pandang tersebut belum menjelaskan akar yang menjadi latar belakang krisis di Arakan State.
Mempertanyakan keabsahan pandangan yang melihat krisis kemanusiaan di Arakan State disebabkan oleh konflik antar agama, tidak terlampau sulit. Kita dapat melihat kondisi umat Islam di negara bagian Myanmar lain apakah mengalami diskriminasi seperti di Arakan State atau justru hidup tenang tanpa gangguan6). Dalam pemberitaan mengenai kondisi di Myanmar sampai saat ini, terlihat krisis yang terjadi hanya di wilayah Arakan State.
Untuk itu, mengatakan krisis kemanusiaan ini disebabkan oleh pembantaian umat Budha terhadap umat Islam tidak benar-benar tepat. Kebetulan Rohingya merupakan etnis bermayoritas Muslim dan kebetulan mereka berada di Arakan State wilayah yang kerap berkonflik di Myanmar. Untuk itu, agama bukan faktor yang melatarbelakangi konflik.
Selanjutnya mempertanyakan keabsahan dalil politik penguasan Migas di Arakan State sebagai latar belakang konflik mungkin tidak mudah. Hal ini karena analisa ini sepenuhnya tidak salah. Memang adanya keinginan untuk menguasai kekayaan alam di Arakan State menyebabkan krisis ini semakin parah. Namun, benarkah krisis kemanusiaan di Arakan State di latar belakangi oleh politik Migas semata? Atau justru politik Migas hanya memperparah keadaan, bukan merupakan faktor kunci krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya?
Secara garis besar tulisan ini berisikan pandangan penulis yang mengajak pembaca melihat krisis kemanusiaan di Arakan State akibat ketidaksetaraan perlakuan negara terhadap minoritas dan masyarakat yang dianggap bukan penduduk pribumi. Perlu diingat label minoritas yang didapatkan oleh Rohingya karena etnis bukan karena agama.
DARI PERUBAHAN KONSTITUSI KEMUDIAN BERAKIBAT PADA DELIGITIMASI KEWARGANEGARAAN
Seperti diketahui bersama, Rohingya bukanlah masyarakat asli Myanmar. Rohingya dibawa masuk kedalam wilayah Myanmar oleh pemerintah kolonial Inggris yang menguasai Myanmar pada tahun 18267). Secara etnis, Rohingya merupakan keturunan Bengali, yang sekarang banyak mendiami negara Bangladesh. Sampai saat ini pemerintah Myanmar masih melihat Rohingya sebagai penduduk ilegal asal Bangladesh.
Dalam hukum kolonial Inggris, Rohingya dimasukkan kedalam etnis yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, kondisi ini berubah ketika Myanmar merdeka lalu mengganti konstitusi negara sehingga Rohingya dikeluarkan dari etnis resmi Myanmar. Meski pada tahun 1950 istilah Rohingya sebagai etnis sempat di akui pada pemerintahan U Nu, namun ketika Militer Myanmar berkuasa pada tahun 1962, situasi mulai berubah.
Konstitusi baru yang dibentuk pada 1974, merupakan awal mimpi buruk nasib Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya mulai kehilangan status kewarganegaraan dibawah rezim militer. Tidak sampai disitu, pada tahun 1982, Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang meletakkan Rohingya sebagai pendatang asing. Kuatnya upaya pembentukan identitas nasional yang tidak memberi tempat bagi Rohingya sebagai “orang asli” Myanmar menjadi alasan kuat lahirnya kebijakan diskriminatif tersebut. Pemberlakuan Adaptation of Expressions Law Nomor 15 Tahun 19898) yang merubah nama Arakan menjadi Rakhine mempertegas upaya pembentukan identitas negara bermayoritas Budha.
Konflik di Arakan State tercatat terjadi pertama sekali pada tahun 1970an dan kembali terulang pada tahun 1990an. Kalau dilihat, rangkaian konflik yang terjadi beriringan dengan lahirnya kebijakan yang mengasingkan Rohingya dari kewarganegaraan resmi. Diamnya negara dalam pembantaian etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar pada pada tahun 2012-2013, menguatkan posisi negara yang tidak seimbang dalam melihat konflik di Arakan. Terlebih sejak kartu identitas putih yang dipegang Rohingya dihapus pada tahun 2015. Maka, jalan keluar yang selalu diambil oleh etnis Rohingya adalah keluar dari Arakan dan menjadi pengungsi di negara lain.
Hingga saat ini, kita masih dapat melihat sikap jelas pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Meski Aung San Su Kyi, mendeklarasikan pemerintahannya lebih demokratis, namun Su Kyi tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait posisi etnis Rohingya sebagai etnis resmi dalam konstitusi Myanmar.
Status kewarganegaraann yang tidak sah, menyebabkan posisi etnis Rohingya dihadapan konstitusi Myanmar tidak diakui secara penuh. Adanya delegitimasi hak warga negara yang dialami etnis Rohingya menjadikan kondisi Rohingya kian tersisih dihadapan negara. Posisi ini kemudian menjadikan Rohingya sangat mudah mengalami tindakan diskriminatif, terutama dari pihak militer dan ekstrimis Budha.
MEMPERDALAM ANALISA DALAM MELIHAT KONFLIK DI ARAKAN STATE DAN UPAYA ADVOKASI KEDEPAN
Menggiring analisa krisis kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya karena identitas agama, tidak memberi keuntungan berarti. Hal ini karena mudah dipatahkan dengan perbandingan kondisi umat muslim di negara bagian lain yang tidak mengalamai diskriminasi dari pemerintah maupun etnis mayoritas Myanmar. Begitupun dalam upaya melihat krisis ini terjadi karena adanya politik Migas, akan mempersempit persoalan pada konflik aset semata. Dua cara pandang tersebut menutup mata kita dalam melihat persoalan yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan status warga negara dalam konstitusi Myanmar.
Intervensi terhadap Migas di Myanmar baru terjadi pada tahun 2000-an ketika Tiongkok mulai tertarik pada kekayaan energi di Arakan pada tahun 2004. Pipa gas milik Tiongkok kemudian selesai dikerjakan pada tahun 20139). Begitupun dengan intervensi Soros yang baru di mulai pada tahun 2003 dan semakin intens setelah tahun 2012 dimana upaya men-demokrasi-kan Myanmar mulai bergaung10).
Kalau melihat dari kacamata politik Migas, maka konflik yang terdekat sejak intervensi tersebut ialah pada tahun 2012. Pada saat itu konflik diyakini bermula setelah sekelompok pria etnis Rohingya dituduh memperkosa dan membunuh wanita Budhis. Konflik ini kemudian menjalar menjadi konflik antar entis di Rakhine (nama Arakan State setelah 1989). Posisi negara terutama Aung San Su Kyi menjadi dilematis ketika adanya tekanan dari kelompok ekstrim Budhis11). Konflik ini kemudian lebih disorot sebagai konflik antar agama, karena melibatkan ekstrimis Budha dan pejuang muslim Arakan.
Cara pandang ini mengesampingkan konflik-konflik di masa lampau yang sudah lebih dahulu sering terjadi. Melihat dari cara pandang diatas, konflik pada tahun 1970an dan 1990an, tidak bisa dianggap terjadi karena adanya politik Migas. Untuk, itu persoalan krisis di Arakan jauh lebih luas dan krusial ketimbang politik Migas maupun agama.
Sejatinya, persoalan utama etnis Rohingya adalah adanya delegitimasi hak konstitusi kewarganegaraan. Kondisi ini terjadi karena adanya pegaruh kuat negara dalam membentuk identitas negara. Dalam persoalan Myanmar, pembentukan identitas negara nasionalis-budhis menjadi sebab lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut. Terlebih ketika upaya pembentukan identitas nasional dibantu oleh kekuatan militer yang kuat.
Hak yang dicabut ini kemudian menghilangkan kesempatan Rohingya untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang setara dan sama dihadapan negara. Pemisahan sikap pemerintah Myanmar ketika konflik pecah menandai hal tersebut. Hilangnya hak-hak konstitusi Rohingya menyebabkan Myanmar tidak melakukan upaya perlindungan bagi Rohingya.
Upaya negara-negara di ASEAN untuk menciptakan kondisi politik yang menyetarakan warga negara di Myanmar tidak bisa dilakukan dengan mengintervensi negara tersebut. Hal ini karena ASEAN memiliki prinsip yang tidak bisa mengintervensi politik negara anggota. Meskipun PBB memiliki intrumen Responsibility to Protect, namun negara-negara di ASEAN seperti Indonesia masih terikat dengan prinsip non-intervensi ASEAN12).
Terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada tahun 2014 dapat dilihat sebagai upaya negara-negara ASEAN yang ingin melihat negara ini merubah kebijakan politik kearah yang lebih demokratis dan bebas diskriminatif. Namun, perubahan nasib Rohingya di Arakan masih belum terjadi, karena pihak Militer masih menguasai pemerintahan Myanmar. Pemerintahan Aung San Su Kyi pun kini masih terkurung oleh kekuatan Militer yang masih sangat kuat. Usaha yang patut diberi apresiasi ialah dibentuknya Advisory Commision on Rakhine State yang di ketuai oleh Kofi Annan. Setidaknya ada sedikit kemajuan pemerintahan Aung San Su Kyi dengan memberi sedikit harapan terhadap konflik di Arakan State.
Dalam praktiknya tentu keberadaan komisi yang diketuai oleh Kofi Annan belum memadai perubahan di Myanmar. Untuk itu, negara-negara ASEAN perlu melakukan langkah advokasi dengan memperkuat basis civil society di dalam negara Myanmar. Civil society diharapkan menjadi alternatif yang dapat merubah Myanmar dari dalam. Perlu untuk memperkuat keberadaan civil society di Myanmar yang bekerja langsung di akar rumput, dan tidak memiliki kecenderungan politik.
Metta Development Foundation yang dipimpin oleh Lehpai Seng Raw13), dapat dijadikan contoh untuk kemudian melahirkan NGO-NGO sejenisnya, agar perubahan di Myanmar dapat terjadi dari dalam tubuh sendiri. Kekuatan civil society dapat pula membantu kampanye perubahan status kewarganegaraan Rohingya dan menjadikan Rohingya sebagai etnis resmi yang mendapatkan tentangan dari kubu nasionalis-budhis yang sudah lama berkuasa di Myanmar.
– Yogi Febriandi* –

Disclaimer: Pendapat dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mesti mewakili pendapat atau pandangan padébooks.com
Sumber gambar tajuk sebelum olah digital: wikimedia dengan lisensi CC0.